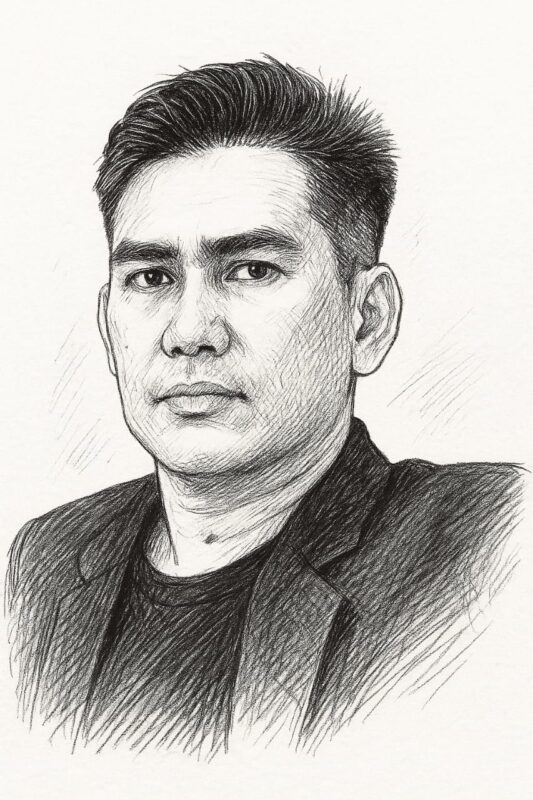Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama Dewan Pers
SEJARAH mencatat, di setiap masa peradaban, pers selalu hadir sebagai saksi dan pengingat. Di Indonesia, perjalanan bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran para jurnalis, mulai dari zaman pergerakan nasional hingga era digital saat ini. Surat kabar seperti Medan Prijaji yang dipelopori Tirto Adhi Soerjo, atau tulisan-tulisan kritis tokoh pergerakan yang dimuat di media cetak awal abad ke-20, menjadi bagian dari bara api kebangkitan bangsa.
Hingga kini, peran itu tetap sama pentingnya. Pers adalah “nafas demokrasi” yang menjaga agar kekuasaan tetap berpijak pada nurani rakyat. Di tengah derasnya arus politik praktis yang kerap membelokkan akal sehat, jurnalis dituntut hadir bukan sebagai bagian dari permainan, melainkan sebagai penonton yang kritis sekaligus wasit yang jujur.
Namun, menjadi wasit yang jujur tidaklah mudah. Di sinilah letak beratnya tugas seorang jurnalis, ia harus menulis di atas panggung yang dipenuhi sorak-sorai, rayuan, bahkan ancaman.
Kita semua paham, politik di negeri ini seringkali penuh drama. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, banyak aktor politik justru sibuk memperkuat kepentingan kelompok. Persoalan korupsi, oligarki, dan polarisasi politik seolah menjadi makanan sehari-hari.
Dalam situasi seperti ini, pers menghadapi ujian yang berat. Tidak jarang media digiring menjadi alat propaganda. Tidak jarang pula jurnalis dipaksa tunduk oleh tekanan ekonomi dan politik. Inilah tantangan besar kita, bagaimana tetap menjaga independensi dan keberanian, sekaligus tetap berada dalam jalur yang penuh integritas.
Karya jurnalistik yang sejati adalah karya yang lahir dari keberanian. Berani menulis apa adanya, berani menolak manipulasi, dan berani berdiri di sisi rakyat yang kerap tak punya suara. Jika pers kehilangan keberanian, maka ia bukan lagi lentera, melainkan sekadar cermin buram yang memantulkan kepalsuan.
Di balik semua tantangan itu, ada satu kata kunci yang sering terlupakan yakni istiqomah. Istiqomah bukan sekadar konsisten, melainkan keteguhan hati untuk tetap berada di jalan yang benar meski godaan dan rintangan datang bertubi-tubi.
Seorang jurnalis yang istiqomah tidak hanya menjaga tulisannya tetap jujur, tetapi juga menjaga hatinya tetap rendah. Ia tidak merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena bisa menulis atau mengungkap fakta. Sebab, kesombongan adalah racun yang bisa menghapus keberkahan sebuah karya.
Bukankah kita sering melihat, ada orang yang karyanya kecil namun manfaatnya abadi, sementara ada pula yang karyanya besar tetapi segera hilang karena dicemari kesombongan?
Aku pribadi merasa cemburu pada mereka yang pandai menyembunyikan kebaikan. Mereka menolong orang tanpa kamera, menulis tanpa berharap popularitas, bekerja tanpa mengejar tepuk tangan. Dunia mungkin tidak mengenal mereka, tetapi surga merindukan mereka. Dan bukankah itu jauh lebih indah daripada sekadar pujian manusia?
Selain menjaga idealisme, tugas mulia pers adalah menjaga keutuhan bangsa. Indonesia adalah negara besar yang rentan terpecah oleh perbedaan. Di tengah era digital, berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan framing yang menyesatkan dapat dengan cepat membakar emosi publik.
Di sinilah pers harus hadir sebagai pendingin suasana, bukan pemantik api. Pers harus mampu meramu berita yang jernih, mendidik, dan mencerdaskan. Tidak mudah, memang. Terkadang kebenaran tidak seindah judul sensasional. Tetapi jika pers hanya mengejar klik dan sensasi, maka ia sedang memperdagangkan masa depan bangsa.
Jurnalis sejati tidak menulis untuk memecah, melainkan untuk merajut. Tidak menulis untuk menebar kebencian, melainkan untuk memperkuat rasa persaudaraan. Dalam konteks inilah, pers dapat menjadi salah satu perekat NKRI.
Di era media sosial, popularitas seringkali lebih dihargai daripada kualitas. Wartawan pun tergoda menjadi selebritas. Tidak salah, selama tetap pada koridor etika. Namun persoalannya, popularitas seringkali membuat kita lupa tujuan.
Berapa banyak tulisan yang sengaja dibuat provokatif demi viral, meski merugikan banyak pihak? Berapa banyak wartawan yang lebih sibuk membangun citra pribadi daripada mendalami fakta?
Di sinilah pentingnya kembali merenung, siapa sebenarnya yang kita layani? Rakyat atau algoritma media sosial? Kebenaran atau sekadar angka “like” dan “share”? Jika kita tidak berhati-hati, maka kita hanya akan menjadi pedagang kata, bukan lagi penjaga kebenaran.
Seorang filsuf pernah berkata, “Kata-kata yang keluar dari hati akan sampai ke hati, sementara kata-kata yang lahir dari kepura-puraan hanya berhenti di telinga.”
Jurnalisme sejati adalah jurnalisme yang lahir dari hati. Setiap kalimat yang ditulis dengan niat tulus akan abadi. Ia mungkin tidak dibayar mahal, mungkin tidak viral, mungkin tidak masuk “trending topic”, tetapi ia akan terus hidup dalam hati pembacanya.
Dan itulah sejatinya keabadian kata. Sebuah keabadian yang jauh lebih berharga daripada popularitas sesaat.
Menjadi jurnalis yang istiqomah memang bukan jalan mudah. Ia adalah jalan sunyi yang penuh godaan. Godaan kekuasaan, godaan materi, godaan popularitas. Tetapi di situlah letak kemuliaannya.
Pers yang sejati adalah pers yang bekerja dalam diam, menulis dengan ikhlas, menyampaikan dengan jujur, dan membiarkan sejarah yang menilai. Karena pada akhirnya, jurnalisme bukan tentang siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling tulus.
Selamat bekerja, para penggiat pers. Mari kita rawat keutuhan bangsa dengan karya jurnalistik yang jernih, tajam, dan penuh cinta pada negeri ini. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah, menjaga hati tetap rendah, dan menulis kata-kata yang kelak dirindukan bukan hanya oleh bangsa ini, tetapi juga oleh surga. (*)